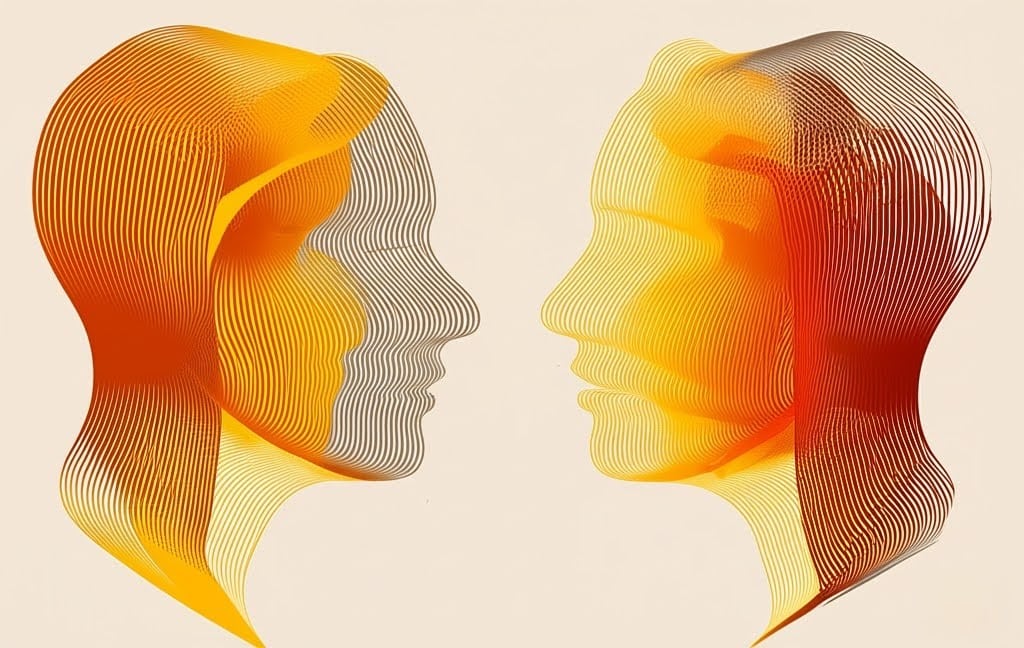Pernahkah kamu, sepertiku, duduk di meja makan keluarga, di tengah riuhnya tawa dan obrolan, namun tiba-tiba suasana berubah tegang? Sebuah topik sensitif terlempar, entah itu soal pilihan karir yang dianggap “tidak realistis” oleh orang tua, atau ide-ide baru bagaimana hidup seharusnya dijalani. Kamu merasa punya argumen yang kuat, data yang valid, dan sudut pandang yang jelas-jelas benar. Tapi, mengapa rasanya seperti ngobrol sama tembok ? Mengapa perdebatan itu tak berujung, dan frustasi justru yang meluap?
Aku pernah persis di posisi itu. Bertahun-tahun, aku hidup dengan keyakinan bahwa kebenaran itu tunggal, seperti garis lurus yang harus kita ikuti. Jika aku punya fakta, jika aku punya logika, maka aku “benar,” dan yang lain “salah.” Pola pikir ini, tanpa kusadari, sering kali membuatku lebih banyak berdebat daripada memahami, lebih banyak menghakimi daripada berempati. Hingga suatu hari, sebuah pertanyaan sederhana muncul di benakku: Apa sebenarnya hakikat kebenaran itu?
Perjalanan ini membawaku pada sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Aku menyadari bahwa mencari kebenaran bukanlah tentang menjadi pemenang dalam argumen, melainkan tentang menjadi lebih bijak, lebih lapang dada, dan lebih terbuka—sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan nilai-nilai luhur tenggang rasa dan gotong royong yang sudah lama mengakar di masyarakat kita.
Mari kita bayangkan lagi meja makan itu, tapi kali ini dengan perspektif yang berbeda. Bukan hanya soal karier, tapi juga tentang katakanlah dampak masif AI terhadap dunia kerja. orang tuamu, yang mungkin menyaksikan PHK massal di tahun ’98, bersikeras bahwa stabilitas adalah segalanya, bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan dan kita harus bersiap dengan pekerjaan yang “aman.” Sementara adikmu, seorang digital native yang tumbuh dengan inovasi, justru melihat AI sebagai peluang tak terbatas untuk menciptakan hal baru, bahkan pekerjaan yang belum ada. Siapa yang benar?
Di sinilah kita mulai melihat lapisan-lapisan kebenaran yang sebenarnya ada di sekitar kita. Ada kebenaran faktual, yang didasarkan pada data objektif tentang proyeksi lapangan kerja, tingkat adopsi AI di berbagai industri, atau bahkan kecepatan internet di kota-kota besar. Ini adalah kebenaran yang bisa diverifikasi secara ilmiah, seperti air yang selalu mendidih pada 100°C di permukaan laut.
Namun, ada pula kebenaran nilai dan pengalaman. Orang tuamu tidak salah, sebab pengalaman pahit krisis ekonomi membentuk “kebenaran” tentang pentingnya keamanan finansial baginya. Adikmu pun tidak salah, karena pertumbuhan di era digital memberinya “kebenaran” tentang potensi kreativitas dan adaptasi. Terkadang, bahkan ada kebenaran kontekstual, seperti seorang nenek yang punya “kebenaran” tentang efektivitas pengobatan herbal turun-temurun untuk penyakit tertentu. Meskipun belum sepenuhnya dijelaskan oleh sains modern, dalam konteks budaya dan pengalaman pribadinya, itu adalah kebenaran yang berfungsi.
Sebagaimana pepatah kuno tentang beberapa orang buta yang meraba gajah, masing-masing menyentuh bagian yang berbeda—belalai, kaki, telinga—dan mendeskripsikan gajah dengan cara yang berbeda pula. Namun, bukan berarti gajah itu tidak ada. Gajah itu nyata, hanya saja perspektif kita yang terbatas yang membuat gambaran kita tidak utuh.
Tantangan ini menjadi semakin kompleks di era digital yang kita alami sekarang. Sayangnya, di era media sosial seperti Instagram, TikTok, atau X, “gajah” kita sering kali tersembunyi di balik dinding algoritma. Aku ingat betapa mudahnya aku terjebak dalam filter bubble saat mulai tertarik dengan investasi kripto dan saham beberapa tahun lalu. Setiap hari, feed-ku dibanjiri konten yang memuji potensi kripto, kisah sukses, dan analisis bullish (seperti kamu ngumpulin alasan kenapa sesuatu bakal naik harganya). Jarang sekali aku melihat perspektif yang mempertanyakan risiko atau mengkritik volatilitasnya, apalagi orang yang jujur memperlihatkan kerugian mereka saat trading atau investasi. Ini menciptakan ilusi bahwa “kebenaran” tentang kripto itu tunggal dan sangat positif.
Algoritma ini tidak peduli dengan kebenaran karena hanya didesain untuk peduli dengan engagement. Dan yang lebih mengerikan, teknologi kini memungkinkan penciptaan deepfake dan manipulasi informasi yang sangat meyakinkan. Video yang dulu kita anggap sebagai “bukti” paling otentik, kini bisa dipalsukan dengan mudah. Aku sering melihat video manipulatif tentang teori konspirasi geopolitik atau “solusi instan” untuk masalah sosial yang tersebar luas di grup-grup chat, lengkap dengan “ahli” yang berbicara atau “testimoni” yang dramatis. Ini menantang cara tradisional kita memverifikasi apa yang nyata.
Yang paling berbahaya adalah ketika kita terjebak dalam echo chamber (ruang di mana kita hanya mendengar gema dari suara kita sendiri). Di grup WhatsApp keluarga besar, misalnya, kita mungkin merasa semakin yakin dengan pandangan politik tertentu, padahal kita sebenarnya tidak pernah benar-benar diuji oleh perspektif yang berbeda. Kita merasa sudah “divalidasi” oleh algoritma atau komunitas, sehingga malas melakukan fact-checking.
Untuk keluar dari bubble ini, aku belajar untuk mencoba beberapa langkah praktis. Pertama, aktif mencari sumber berita dari berbagai sumber yang mana jika biasanya aku baca media yang sejalan dengan pandanganku, aku mulai sesekali membaca yang berbeda sudut pandang. Kedua, bergabung dengan komunitas yang beragam, bukan hanya yang satu pemikiran. Aku ikut diskusi online dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, bahkan yang kadang membuat tidak nyaman.
Pengalaman ini membawaku pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kita membedakan antara kebenaran yang teruji waktu dengan tren yang sedang viral? Nenekku selalu punya ramuan kunyit untuk masalah pencernaan. Itu adalah “kebenaran tradisional” yang diwariskan turun-temurun, berdasarkan pengalaman ratusan tahun. Bertahun-tahun kemudian, sains modern membuktikan bahwa kunyit memang mengandung kurkumin yang memiliki sifat anti-inflamasi. Di sini, kebenaran tradisional dan modern tidak saling bertentangan, justru saling memperkuat.
Sama halnya dengan konsep gotong royong yang sudah mengakar di Indonesia. Apa yang nenek moyang kita ketahui secara intuitif tentang pentingnya kebersamaan, kini terbukti secara ilmiah meningkatkan modal sosial dan ketahanan komunitas. Yang menarik dari kebenaran ilmiah adalah sifatnya yang rendah hati. Ia bisa berubah dengan penemuan baru. Dulu, lemak dianggap musuh utama diet, kini kita tahu ada lemak baik dan lemak jahat. Ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati terhadap pengetahuan yang kita miliki.
Hikmahnya kita bisa menghargai kebenaran tradisional sambil tetap terbuka pada verifikasi dan penyempurnaan melalui metode modern. Tidak semua yang lama itu salah, dan tidak semua yang baru itu benar. Yang penting adalah sikap terbuka untuk terus belajar dan memverifikasi.
Dalam setiap diskusi, kita sering terjebak dalam pola pikir menang-kalah. Aku ingat pernah berdiskusi tentang sistem pendidikan dengan beberapa teman. Satu pihak bersikeras tentang pentingnya disiplin dan struktur, berdasarkan pengalaman sukses mereka dengan sistem tradisional. Pihak lain ngotot tentang pentingnya kreativitas dan critical thinking, berdasarkan tuntutan dunia kerja modern. Keduanya sama-sama merasa benar.
Namun, ada kemungkinan lain yang jauh lebih menarik. keduanya bisa benar sekaligus. Kebenaran bisa bersifat parsial, atau bersifat kontekstual yang mana gaya parenting otoriter mungkin efektif untuk anak tertentu dalam situasi tertentu, sementara gaya permisif cocok untuk yang lain. Bahkan ada kebenaran komplementer yang paradoks, seperti cahaya yang bisa bersifat partikel dan gelombang sekaligus. Dalam hidup, “jadilah dirimu sendiri” dan “beradaptasi dengan situasi sosial” keduanya bisa benar dalam konteks yang berbeda.
Aku belajar untuk mengubah pertanyaan dari “siapa yang benar?” menjadi “apa yang bisa aku pelajari dari sudut pandang ini?”, “dalam situasi apa pendekatan ini paling efektif?”, dan “bagaimana kita bisa memadukan wawasan dari berbagai perspektif?”
Perjalanan pemahaman ini bermula dari refleksi sederhana: mengapa aku dan orang tuaku sering memiliki pandangan yang begitu berbeda tentang hal-hal fundamental seperti definisi kesuksesan atau cara menjalani hidup?
Suatu hari, ketika aku dan orang tua berdebat tentang pilihan karier, aku berhenti sejenak. Aku tidak lagi bertanya “siapa yang benar,” tapi “dari mana sudut pandang ini datang?” Aku mulai melihat orang tuaku, bukan hanya sebagai orang tua yang “kolot,” tapi sebagai seseorang yang tumbuh di masa Orde Baru, menyaksikan ketidakstabilan ekonomi yang membentuk nilai “keamanan di atas segalanya.” Sementara aku, yang tumbuh di era reformasi dan digitalisasi, melihat peluang tak terbatas untuk mengambil risiko kreatif. Keduanya tidak salah. Hanya berbeda konteks pengalaman.
Perubahan mindset ini terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dulu, aku mungkin berpikir “pendapat orang tua kuno dan tidak relevan,” kini aku bertanya “apa hikmah yang bisa aku ambil dari pengalaman hidup mereka?” Dulu, mungkin aku berpikir “generasi muda terlalu idealis dan tidak realistis,” kini aku bertanya “apa energi dan perspektif yang bisa memperkaya pandanganku?”
Yang paling menarik adalah ketika aku menyadari bahwa “menang” dalam argumen tapi tidak belajar apa-apa sebenarnya adalah “menang tanpa apa-apa”, yang bisa juga diartikan sebagai kalah memaknai hidup. Transformasi ini mengubah mindset dari zero-sum (kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah) ke positive-sum (semua pihak bisa untung dan belajar). Ini seperti mengubah diskusi dari adu argumen menjadi eksplorasi bersama.
Dengan pemahaman baru ini, aku menjadi lebih peka terhadap dinamika percakapan. Ada tanda-tanda halus yang bisa kita tangkap ketika diskusi mulai bergeser dari konstruktif menjadi destruktif misalnya nada suara yang mulai meninggi, perubahan bahasa tubuh yang mengindikasikan ketidaknyamanan, mulai menyerang pribadi daripada ide, tidak mendengarkan tetapi hanya menunggu giliran bicara, atau mengulang-ulang poin yang sama dengan intensitas lebih tinggi.
Aku ingat saat mengobrol dengan seorang teman tentang investasi. Awalnya diskusi kami sehat, bertukar analisis tentang saham tertentu. Tapi kemudian, aku perhatikan dia mulai menyampaikan ketidaksetujuannya dengan semangat yang berlebihan, bahkan membawa-bawa track record investasinya di masa lalu untuk “membuktikan” bahwa dia lebih tahu.
Dalam situasi seperti itu, aku belajar untuk tetap menyampaikan alasan di balik pendapatku dengan tenang, tapi kemudian melakukan deeskalasi dengan mengatakan, “Kamu punya poin yang menarik berdasarkan pengalamanmu. Aku juga punya perspektif yang berbeda berdasarkan riset yang aku baca. Mungkin keduanya bisa benar dalam konteks yang berbeda. Yang penting kita berdua tetap hati-hati dalam mengambil keputusan finansial, ya.”
Ini bukan berarti menyerah atau mengalah, tetapi menyelamatkan hubungan dan mengembalikan fokus pada pemahaman, bukan kemenangan. Aku menyadari bahwa mempertahankan persahabatan lebih berharga daripada menang argumen tentang saham.
Salah satu pendekatan yang paling efektif yang kutemukan adalah memberikan perspektif alternatif tanpa memaksakan. Seperti memberikan peta yang lebih lengkap tanpa memaksa mereka berjalan ke arah tertentu. Ini yang aku sebut “Penemuan Terbimbing.”
Dulu Aku punya seorang teman yang sering curhat tentang konflik dengan atasannya, dan dia kerap menyalahkan si atasan karena merasa diabaikan yang mana kondisi dia yang sedang mengerjakan pekerjaan. Alih-alih langsung bilang, “mungkin kamu juga ada salahnya,” aku mencoba pendekatan ini. Aku bilang, “Wah, pasti frustrasi banget ya. Coba deh, kalau kamu jadi atasanmu yang lagi di bawah tekanan dari atasannya lagi, kira-kira apa yang mungkin dia pikirkan waktu ambil keputusan itu?”
Dengan pendekatan ini, dia sendiri yang mulai melihat perspektif lain dan menemukan wawasan bahwa mungkin ada faktor-faktor yang tidak dia ketahui. Ketika orang menemukan sesuatu sendiri, mereka akan lebih tulus menerima dan mengintegrasikannya. Ada rasa kepemilikan terhadap wawasan yang mereka temukan, bukan sekadar “disuruh” oleh orang lain. Ini sesuai dengan prinsip dalam psikologi bahwa people support what they help create.
Dalam praktiknya, ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan: “Menarik juga kalau dilihat dari sudut pandang…” “Aku penasaran, kira-kira apa ya yang dia rasakan waktu itu…” atau “Coba bayangkan kalau kita di posisinya…” Kunci utamanya adalah genuine curiosity, bukan manipulasi untuk memaksa orang mengubah pandangan. Meskipun dalam praktiknya aku menyadari ini tidak semudah berteori.
Dalam menjelajahi konsep kebenaran, aku juga menemukan bahwa ada dimensi-dimensi lain yang sangat relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Kadang yang penting bukan apakah sesuatu benar secara absolut, tapi apakah itu berguna dan berfungsi dalam hidup kita.
Konsep basa-basi dalam budaya Jawa, misalnya, mungkin tidak efisien menurut standar Barat, tapi memiliki fungsi sosial yang krusial untuk membangun hubungan dan menghindari konfrontasi langsung. Ini adalah kebenaran pragmatis dalam konteks budaya. Ketika kita bertanya “sudah makan belum?” kepada tetangga, secara faktual mungkin kita tidak benar-benar ingin tahu menu makan siangnya. Tapi secara sosial, itu adalah cara kita menunjukkan perhatian dan membangun kedekatan.
Dalam hubungan, terutama di budaya Indonesia yang menghargai harmoni, kebenaran emosional sering sama pentingnya dengan kebenaran faktual. Ketika seorang istri berkata kepada suaminya, “kamu enggak pernah bantuin aku,” mungkin secara faktual suami sudah membantu 30% pekerjaan rumah. Tapi kebenaran emosional si istri adalah dia merasa kewalahan dan butuh lebih banyak dukungan. Kedua kebenaran ini valid dan perlu diatasi.
Ada pula kebenaran interpersonal dalam nilai gotong royong. Dalam komunitas, kebenaran bukan hanya soal fakta, tapi juga tentang kejujuran, kepercayaan, dan pemahaman timbal balik yang membangun. Konsep tenggang rasa mengajarkan kita bahwa ada cara menyampaikan kebenaran yang menghormati perasaan orang lain tanpa mengorbankan substansi. Ini bukan tentang berbohong, tapi tentang waktu, konteks, dan cara penyampaian yang bijak.
Mungkin yang terpenting dari semua pembelajaran ini adalah belajar nyaman dengan ketidakpastian—sesuatu yang sangat relevan di era yang penuh dengan perubahan cepat ini. Aku sadar bahwa tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa pilihan karier tertentu akan sukses 10 tahun ke depan, atau bahwa ada panduan manual sempurna untuk membesarkan anak.
Ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan teman. Kita bisa hidup bermakna dan membuat keputusan baik bahkan ketika kita tidak yakin 100% tentang kebenaran mutlak. Keberanian untuk bertindak dalam ketidakpastian, sambil tetap terbuka untuk belajar dan berubah, mungkin adalah kebijaksanaan yang lebih praktis daripada mencari kepastian absolut.
Kerangka kerja yang kubangun untuk hidup dengan ketidakpastian cukup sederhana: mengumpulkan informasi terbaik yang tersedia, tapi jangan terjebak dalam analysis paralysis. Membuat keputusan berdasarkan nilai dan prinsip, bukan hanya data. Tetap terbuka terhadap umpan balik dan penyesuaian. ego jangan sampai menghalangi pembelajaran. Dan fokus pada apa yang bisa aku kendalikan, melepaskan yang di luar kendali kita. Lagi lagi stoa. (Suatu saat mungkin aku akan membahas stoa dalam pandangan Islam yang mana lebih dekat artinya dengan tasawuf karena ada sisi spiritualnya).
Lanjut, contoh konkretnya, ketika aku harus memutuskan pindah kerja beberapa tahun lalu, aku tidak menunggu sampai punya 100% kepastian tentang prospek industri baru itu. Aku kumpulkan informasi sebanyak mungkin, konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman, tapi pada akhirnya aku ambil keputusan berdasarkan alignment dengan nilai-nilai dan visi jangka panjangku. Hasilnya memang tidak selalu sesuai ekspektasi, tapi proses pembelajarannya sangat berharga.
Aku juga merasa penting untuk mengakui bahwa pendekatan “semua perspektif valid” tidak selalu tepat. Ada situasi di mana kita perlu tegas dan tidak kompromistis. Contohnya, fakta sains dasar seperti bumi itu bulat, atau pentingnya menjaga privasi data di era digital berdasarkan regulasi dan etika yang berlaku, bukanlah soal perspektif.
Hak asasi manusia fundamental seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan larangan kekerasan adalah kebenaran universal. Begitu pula isu keadilan: korupsi tetap salah, terlepas dari perspektif budaya atau posisi sosial. Aku belajar untuk waspada ketika relativitas digunakan untuk justifikasi bahaya terhadap orang lain, atau ketika penyangkalan terhadap fakta ilmiah bisa membahayakan kesehatan publik atau lingkungan.
Dalam diskusi tentang praktik penyuapan dalam bisnis, misalnya, kita tidak bisa bilang “itu kan budaya di sini” atau “dari perspektif si pengusaha, itu cara bertahan hidup.” Ada standar etika universal yang perlu ditegakkan. Relativitas kebenaran harus punya batas yang jelas ketika menyangkut harm terhadap orang lain atau society secara keseluruhan.
Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kebenaran bukanlah sebuah tujuan akhir yang statis, bukan sebuah garis finish yang bisa kita capai dan kemudian berhenti. Ia adalah sebuah perjalanan yang dinamis, sebuah sungai yang terus mengalir, penuh dengan pembelajaran, empati, dan pertumbuhan. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memahami diri, orang lain, dan dunia di sekitar kita.
Mungkin, kebenaran sejati terletak pada keberanian untuk terus bertanya, untuk terus mendengarkan, dan untuk terus merangkul ketidakpastian. Setiap interaksi, setiap perbedaan pandangan, adalah kesempatan untuk memperkaya diri dan hubungan kita.
Dan ketika aku kembali duduk di meja makan keluarga itu, dan ketika topik sensitif kembali terlempar—mungkin tentang AI, tentang investasi, atau tentang cara mendidik anak—aku tidak lagi merasa frustasi. Aku tidak lagi bicara dengan tembok. Sebaliknya, aku mendengar suara-suara yang sebelumnya tersembunyi: kekhawatiran di balik resistensi orang tua terhadap teknologi, optimisme yang tulus di balik antusiasme adik tentang masa depan, atau bahkan kebijaksanaan yang terkandung dalam ramuan kunyit nenek dulu.
Meja makan itu kini bukan lagi medan pertempuran untuk membuktikan siapa yang benar. Itu adalah aku menyebutnya ruang lab kehidupan, tempat di mana berbagai kebenaran bertemu, berinteraksi, dan menciptakan pemahaman yang lebih kaya. Tawa dan obrolan masih riuh, tapi kini ada lapisan yang lebih dalam. Sebuah apresiasi terhadap kompleksitas kehidupan dan keragaman perspektif yang membuat hidup ini begitu berwarna.
Mari kita terus melangkah dalam perjalanan ini, dengan hati yang terbuka dan telinga yang mendengarkan, menemukan makna yang lebih dalam di setiap tikungan, di setiap meja makan, di setiap percakapan yang menantang kita untuk tumbuh. Aku Jati dan terima kasih sudah membaca sampai akhir 🙂
Note: artikel ini adalah hasil pemikiran ku tentang apa itu kebenaran dan dinamika disetiap perdebatan. Ini murni opini pribadi dan aku menyadari masih banyak ruang untuk terus belajar.